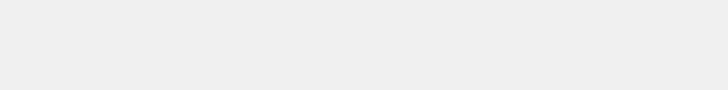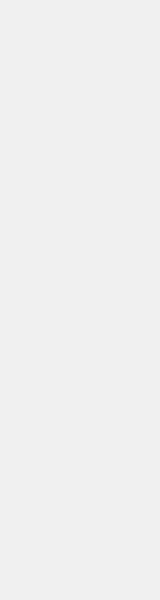Pencarian resep kue cucur yang sempurna, berciri manis legit dan bersarang di bagian tengah, bukan sekadar eksplorasi kuliner, melainkan pencarian terhadap teknik otentik yang telah diwariskan lintas generasi di Indonesia, dengan akar sejarah yang membentang hingga abad ke-18. Kue tradisional ini, yang keberadaannya telah tercatat dalam naskah kuno Serat Centhini, menuntut presisi dalam komposisi bahan dan metode penggorengan untuk mencapai tekstur berserat dan rasa karamel khas gula merah yang menjadi daya tariknya. Kehadirannya bukan sekadar camilan; kue cucur juga mengemban makna filosofis mendalam dalam berbagai upacara adat di Nusantara, mencerminkan harapan akan kemakmuran, keberkahan, keutuhan, bahkan simbol cinta di beberapa budaya.
Asal-usul kue cucur diyakini berakar dari budaya kuliner masyarakat Betawi, meskipun varian serupa dapat ditemukan luas di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Nama "cucur" sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Jawa atau Betawi yang berarti "mengucur" atau "menetes", merujuk pada teknik menuangkan adonan ke dalam minyak panas. Dalam tradisi Betawi, kue ini acap kali dihidangkan dalam perayaan pernikahan, khitanan, dan syukuran kelahiran, sementara di Gorontalo dikenal sebagai "tutulu" dan menjadi pelengkap acara adat dengan pinggiran yang menengadah sebagai simbol permohonan doa. Di Kalimantan Tengah, kue cucur digunakan dalam upacara hinting pali sebagai sesaji, dan di Sulawesi, hadir dalam ritual panen padi serta pembuatan perahu tradisional. Bentuknya yang bulat dengan bagian tengah tebal dan pinggiran tipis berserat, melambangkan inti kehidupan yang kuat dan keseimbangan dalam hidup.
Mencapai karakteristik "bersarang" pada kue cucur merupakan hasil dari serangkaian langkah teknis yang krusial. Praktisi kuliner tradisional menekankan pentingnya konsistensi adonan yang tidak terlalu kental atau encer, perbandingan tepung beras dan tepung terigu yang tepat, serta peran gula merah berkualitas untuk rasa legit. Setelah pencampuran, adonan memerlukan waktu istirahat yang cukup, bervariasi antara 15 menit hingga 5 jam, yang memungkinkan adonan untuk lebih mengembang dan bersarang saat digoreng. Proses penggorengan juga sangat spesifik: menggunakan wajan kecil berbentuk cekung dengan jumlah minyak yang tidak terlalu banyak namun cukup untuk merendam adonan. Api harus dijaga dalam kondisi sedang cenderung kecil. Koki Veronica Dhani, penulis buku resep, menggarisbawahi bahwa penggunaan minyak yang sedikit saat menggoreng adalah kunci utama untuk mendapatkan serat pada kue cucur, sementara Tuti Soenardi menekankan pentingnya minyak yang sudah panas. Setelah adonan dituangkan, teknik menyiram-nyiram bagian tengah kue dengan minyak panas secara berulang adalah esensial untuk memicu pembentukan serat unik yang menjadi ciri khasnya.
Meskipun kue cucur terus digemari, eksistensinya menghadapi tantangan di tengah gempuran kuliner modern. Kurangnya peminat di kalangan generasi muda, persaingan dengan makanan cepat saji, dan berkurangnya generasi penerus penjual tradisional menjadi masalah utama. Upaya pelestarian dan pengembangan saat ini berfokus pada inovasi rasa, bentuk, dan kemasan, serta promosi melalui media sosial dan penyelenggaraan lokakarya untuk menarik minat generasi muda. Contohnya, kue cucur kini hadir dalam varian warna hijau pandan, ungu ubi, hingga merah muda, menunjukkan adaptasi tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mempertahankan warisan kuliner, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia yang tetap relevan di era kontemporer.