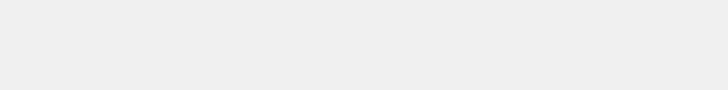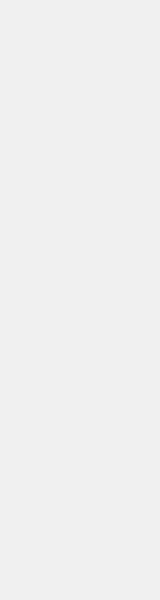Seorang jurnalis bernama Steven mendapati resep hidangan "hemat budget" yang ia bagikan di media sosial disamakan dengan makanan kucing, memicu perdebatan daring tentang realitas ekonomi dan persepsi sosial terhadap pilihan kuliner sederhana. Insiden ini, yang menjadi sorotan pada September 2022, menyoroti tantangan yang dihadapi individu dalam menyeimbangkan keterjangkauan dengan ekspektasi kuliner di tengah kenaikan biaya hidup.
Resep Steven, yang ia sebut sebagai menu ekonomis, terdiri dari tuna kalengan, saus mustard pedas, sereal tinggi serat, dan acar. Kombinasi bahan-bahan tersebut, meskipun fungsional dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan biaya rendah, secara cepat memicu perbandingan negatif dari warganet. Stigma terhadap makanan yang dianggap murah atau tidak konvensional bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejarawan kuliner dan ahli antropologi telah lama mencatat bagaimana bahan pangan lokal seperti singkong dan ubi jalar, yang kaya karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral, pernah dianggap sebagai "makanan kampung" atau dikaitkan dengan status sosial rendah, bahkan hingga saat ini di beberapa kalangan. Demikian pula, tempe, yang kini diupayakan untuk diakui sebagai Warisan Budaya UNESCO, sempat lama dipandang sebagai "makanan murah" atau kelas dua, meskipun merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi yang menopang gizi rakyat sejak lama.
Tekanan ekonomi turut membentuk pilihan pangan masyarakat. Data Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 menunjukkan bahwa biaya hidup rata-rata rumah tangga per bulan di DKI Jakarta mencapai Rp14,88 juta, meningkat Rp1,43 juta dibandingkan 2018. Kenaikan biaya hidup ini menempatkan Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia, jauh melampaui standar hidup layak yang ditetapkan Badan Pusat Statistik sekitar Rp1,02 juta per bulan pada 2024, sebuah angka yang dinilai tidak sesuai realitas oleh banyak pihak. Meskipun tidak ada data spesifik mengenai rata-rata gaji jurnalis secara nasional yang terbaru, profesi ini seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran pribadi. Kondisi ini memaksa banyak individu, termasuk jurnalis, untuk mencari opsi makanan yang paling efisien dari segi biaya.
Ahli gizi menegaskan bahwa makanan sehat dan bergizi tidak selalu harus mahal. Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Hardinsyah, pernah menyatakan pada tahun 2018 bahwa dengan belanja dan memasak sendiri, seseorang dapat makan sehat per hari dengan biaya sekitar Rp35.000, dengan menu seperti nasi goreng telur untuk sarapan, dan ikan lele serta sayuran untuk makan siang dan malam. Senada, Radyan Yaminar, S. Gz., ahli gizi dari Rumah Sakit Nirmala Suri, pada Juli 2024 juga mengungkapkan bahwa makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, vitamin, dan mineral, dapat dijangkau dengan harga murah, memberikan contoh menu seperti nasi putih, telur dadar, dan tumis buncis dengan perkiraan biaya sekitar Rp7.732,5 per porsi. Dalam konteks ini, kombinasi tuna kaleng dan sereal tinggi serat yang dipilih Steven dapat dipandang sebagai sumber protein dan serat yang memadai, meskipun presentasinya kurang menarik di mata sebagian orang.
Perbandingan dengan makanan kucing, meski bernada merendahkan, secara teknis memiliki beberapa nuansa. Makanan kucing, meskipun aman jika tertelan manusia karena terbuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya dan sama dengan bahan yang digunakan dalam makanan manusia, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai asupan harian. Ahli diet terdaftar di American Dietetic Association, dr. Dawn Jackson Blatner, menjelaskan bahwa makanan kucing diolah dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi spesifik kucing, yang memiliki proporsi mineral, vitamin A, taurin, dan lemak yang tinggi, berbeda dengan kebutuhan nutrisi manusia. Konsumsi makanan kucing secara berlebihan oleh manusia dapat menyebabkan ketidakseimbangan mineral atau keracunan vitamin A. Oleh karena itu, perbandingan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk mencela, secara implisit menyoroti perbedaan gizi yang fundamental antara spesies.
Insiden ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara realitas ekonomi yang mendorong pilihan makanan "hemat budget" dan persepsi sosial yang kerap menghakimi. Ini bukan sekadar tentang resep, melainkan refleksi dari isu yang lebih luas mengenai akses terhadap pangan layak, dignitas dalam memilih makanan, serta peran media sosial dalam mempercepat dan memperluas penilaian publik. Di era ketika konsumsi rumah tangga di Indonesia masih menjadi sorotan, dengan pertumbuhan konsumsi yang hanya 4,93% tahun-ke-tahun pada Kuartal II-2024, diskusi mengenai makanan murah dan bergizi semakin relevan. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa nilai gizi tidak selalu berkorelasi langsung dengan harga atau estetika, dan bahwa kebutuhan untuk "hemat budget" adalah realitas bagi banyak orang. Pergeseran pola konsumsi menuju pangan instan dan homogenisasi menu di kota-kota besar telah mengubah cara manusia memaknai makanan, dari ruang kebersamaan budaya menjadi rutinitas cepat untuk memenuhi kebutuhan biologis. Stigma terhadap makanan murah, sebagaimana pengalaman Steven, menunjukkan perlunya reevaluasi kolektif terhadap nilai dan makna makanan di luar sekadar citra permukaan.